Wednesday, August 02, 2006
 Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki karya sastra yang telah mendunia, La Galigo. Ironisnya, naskah kuno yang berisi konsep kehidupan masyarakat Bugis ini tidak begitu dikenal di tanah air. Di kalangan masyarakat Bugis, naskah kuno terpanjang di dunia ini, masih bisa bertahan karena adanya upaya penyebaran isinya secara turun temurun. Baik melalui tradisi tulis maupun lisan.
Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki karya sastra yang telah mendunia, La Galigo. Ironisnya, naskah kuno yang berisi konsep kehidupan masyarakat Bugis ini tidak begitu dikenal di tanah air. Di kalangan masyarakat Bugis, naskah kuno terpanjang di dunia ini, masih bisa bertahan karena adanya upaya penyebaran isinya secara turun temurun. Baik melalui tradisi tulis maupun lisan.
Seorang massure (baca: masyure) lah yang mampu membacakan sekaligus melantunkan hasil karya sastra ini dengan menggunakan bahasa Bugis kuno. Seorang massure yang berarti pembaca surat, sebetulnya tidak hanya mengambil cerita dari kitab La Galigo, melainkan juga dari Sure Salenang semacam buku cerita rakyat Suku Bugis .
Itulah salah satu bait cerita yang diambil dari kitab La Galigo, yang mengandung makna serta nilai-nilai kesatriaan , tatakrama, kearifan budaya yang diselingi dengan perilaku kehidupan yang romantis.
Saat ini keberadaan massure di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Wajo, yang merupakan mayoritas Suku Bugis bisa dikatakan sudah langka. Tidak banyak orang Bugis yang bisa mengucapkan, memahami dan mengerti bahasa Bugis kuno.
Seorang massure tidak hanya sendirian dalam membacakan surat. Massure selalu didampingi seorang pemain kecapi. Bahkan dalam satu pertunjukan, baik di istana kerajaan maupun acara pernikahan, adakalanya didampingi seorang penterjemah bahasa Bugis kuno, agar para penonton bisa memahami makna surat yang dibacakan massure.
Namun kini sejak 2 tahun terakhir pertunjukan mulai dimodifikasi. Seorang massure tidak hanya diiringi kecapi, melainkan telah ditambah alat musik lain seperti suling, biola, gandrang dan alat musik petik lain yang disebut mandolin, mirip seperti perahu sebagai lambang kemashuran Suku Bugis yang dikenal sebagai pelaut ulung. Namun demikian, tetap kecapi yang memegang peranan penting.
Kolaborasi berbagai alat musik dengan massure ini dilakukan semata-mata untuk membuat pertunjukan lebih menarik. Keterbatasan alat musik kecapi yang hanya memiliki dua senar dengan kemampuan satu oktaf, diakui membuat pertunjukan terasa monoton.
Penambahan berbagai instrumen musik ini adalah upaya yang patut dihargai. Karena bagaimanapun, sebuah karya sastra hanya bisa dinikmati bila dikemas dengan apik. Tentu saja upaya ini pun diiringi harapan munculnya massure generasi baru, sehingga salah satu warisan sastra dunia ini tidak hilang di justru di tanah airnya sendiri.
sumber : indosiar.com
Itulah salah satu bait cerita yang diambil dari kitab La Galigo, yang mengandung makna serta nilai-nilai kesatriaan , tatakrama, kearifan budaya yang diselingi dengan perilaku kehidupan yang romantis.
Saat ini keberadaan massure di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Wajo, yang merupakan mayoritas Suku Bugis bisa dikatakan sudah langka. Tidak banyak orang Bugis yang bisa mengucapkan, memahami dan mengerti bahasa Bugis kuno.
Seorang massure tidak hanya sendirian dalam membacakan surat. Massure selalu didampingi seorang pemain kecapi. Bahkan dalam satu pertunjukan, baik di istana kerajaan maupun acara pernikahan, adakalanya didampingi seorang penterjemah bahasa Bugis kuno, agar para penonton bisa memahami makna surat yang dibacakan massure.
Namun kini sejak 2 tahun terakhir pertunjukan mulai dimodifikasi. Seorang massure tidak hanya diiringi kecapi, melainkan telah ditambah alat musik lain seperti suling, biola, gandrang dan alat musik petik lain yang disebut mandolin, mirip seperti perahu sebagai lambang kemashuran Suku Bugis yang dikenal sebagai pelaut ulung. Namun demikian, tetap kecapi yang memegang peranan penting.
Kolaborasi berbagai alat musik dengan massure ini dilakukan semata-mata untuk membuat pertunjukan lebih menarik. Keterbatasan alat musik kecapi yang hanya memiliki dua senar dengan kemampuan satu oktaf, diakui membuat pertunjukan terasa monoton.
Penambahan berbagai instrumen musik ini adalah upaya yang patut dihargai. Karena bagaimanapun, sebuah karya sastra hanya bisa dinikmati bila dikemas dengan apik. Tentu saja upaya ini pun diiringi harapan munculnya massure generasi baru, sehingga salah satu warisan sastra dunia ini tidak hilang di justru di tanah airnya sendiri.
sumber : indosiar.com



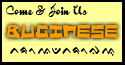


Sedih juga melihat kurangnya kepedulian generasi muda akan kekayaan budaya negaranya sendiri. Apakah ini penyakit malu akan budaya sendiri yang begitu mudahnya dianggap kampungan dan kurang 'keren' dibanding budaya impor? Apakah bukan seharusnya kita yang malu pada org2 bule yang justru tertarik dan jatuh cinta pada kebudayaan Indonesia, yang hanya dengan bermodalkan pena dan kertas bisa jadi beken diatas hasil cipta intelektual bangsa kita? Benar2 sedih saya membaca artikel ini, but thanks for sharing it.