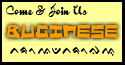Namun tidak seperti kisah nabi Musa di kitab suci, sang Hulppest Commis pribumi tidak lantas kabur dari tanah airnya. Dia memilih tetap tinggal dan siap menerima konsekuensi dari tindakannya yang melanggar etika saat itu. Melawan, apalagi memukuli warga Belanda yang dianggap warga kelas satu adalah kesalahan besar di zaman kolonial itu, apapun alasannya. Kejadian selanjutnya bisa ditebak, sang Hulppest Commis pribumi kemudian didera hukuman administratif; pangkat diturunkan menjadi Agent Welsetboedel Kamer (pegawai rendahan), gaji dipotong hingga tinggal 30%. Dia menerima dengan tenang, dan terbersit rasa puas dalam hatinya. Harga dirinya membela kaumnya sudah ditegakkan, dan itu jauh lebih penting daripada pangkat dan gaji. Nama si Hulppest Commis pribumi berusia 22 tahun itu, Andi Sultan Daeng Raja, putra dari Passari Petta Tanra - Karaeng Gantarang Bulukumba saat itu.
Gantarang, tempat lahir Andi Sultan Daeng Raja, sejak zaman dulu terkenal sebgai penghasil beras utama di sulawesi selatan. Kerajaan Gowa Tallo ketika masa jayanya sangat menggantungkan supply pangannya pada daerah ini. Setelah kemenangan VOC yang didukung oleh Bone dalam perang makassar di pertengahan abad 17, daerah ini sempat diperebutkan antara VOC dan Bone sebagai basis logistik. Tanahnya sangat subur, terhampar seluas 215 km2 dari kaki pegunungan Bangkeng bukit yang dikitari oleh sungai Tangka di utara hingga ke selatan yang bermuara di laut flores. Sungai Tangka yang tak pernah kering itu kemudian dijadikan sumber utama pengairan yang menghidupi persawahan di daerah itu. Secara geopolitik, distrik gantarang adalah wilayah Gowa-Tallo sejak lampau berdasarkan perjanjian Caleppa tahun 1625, penguasanya pun bergelar karaeng, sebuah gelar yang diadaptasi dari kerajaan Gowa-Tallo. Namun sebahagian besar penduduk Gantarang justru menggunakan bahasa bugis sebagai bahasa pengantarnya. Bagi lidah bugis, Gantarang biasanya dituturkan sebagai Gattareng.
Ketika tumbuh sebagai remaja di daerah itu, Andi Sultan yang lahir di Saoraja Gantarang pada 20 mei 1894, mendapati kenyataan yang kontras dengan cerite leluhurnya, daerah Gantarang justru teramat terbelakang, pertanian tidak terurus dan masyarakat petani disana miskin dan tak mampu mengelola sawah dengan baik. Penguasa yang memerintah kala itu pun terkesan abai mengurusi warganya.
Pendidikan dan Jalur Karir
Kondisi rakyatnya yang menyedihkan membuat Andi Sultan tergerak untuk memikirkan bagaimana melakukan perbaikan. Apalagi sejak awal beliau sudah digadang-gadang sebagai pewaris adat Geemeenschaap Gantarang, yang saat itu dijabat secara caretaker oleh paman beliau, Karaeng Cammoa Andi Mappamadeng. Dia kemudian memantapkan tekadnya dengan menekuni pendidikan sebagai bekalnya kelak. Sebagai seorang bangsawan, tidak terlalu sulit baginya untuk memasuki sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial saat itu. Andi Sultan Daeng Raja bahkan mampu duduk di sekolah lanjutan khusus untuk orang eropa kala itu, Eropesche Largerer school (ELS) di Bulukumba. Kemudian dilanjutkan ke sekolah calon ambtenar OSVIA di Makassar tahun 1908. Pada masa sekolah di Makassar inilah, semangat patriotisme dan kemampuan organisasinya mulai terasah dengan mengikuti perkumpulan2 diskusi, terutama karena terpengaruh oleh kebangkitan pergerakan nasional yang dimotori oleh Budi utomo dan Sarekat Islam.
Selepas lulus dari OSVIA di tahun 1914, Andi Sultan Daeng Raja tidak langsung mudik ke Gantarang, tapi memilih meniti karir sebagai ambtenar pada pemerintahan kolonial. Karir nya sebetulnya cukup cemerlang, dengan beberapa kali mendapat promosi hanya dalam waktu singkat. Daerah pengabdiannya cukup luas dan mencakup derah-derah penting di Sulawesi Selatan; bermula dari Pompanua, Sinjai, Takalar, dan berakhir di Campalagian, Mandar. Disela-sela rutinitasnya sebagai pegawai kolonial saat itu, beliau masih menyempatkan diri mengikuti pergerakan nasional yang sedang marak. Mungkin karena aktifitasnya yang dianggap berbahaya waktu itu, dan sikapnya yang kdang-kadang melawan pemerintah, beberapakali Andi Sultan Daeng Raja mengalami demosi dan mutasi yang kurang menguntungkan. Namun semuanya dijalani dengan sabar, sesuai dengan taktik gerakannya waktu itu yang kooperatif. Setelah delapan tahun berkarir sebagai ambtenaar, Andi Sultang Daeng Raja kemudian mengundurkan diri dan memilih untuk mengabdi sepenuhnya untuk rakyat Gantarang. Pada tahun 1922, juga atas desakan nurani demi melihat rendahnya kesejahteraan rakyat Gantarang saat itu, dia kembali ke kampung halaman. Setelah melalui pemilihan formal Ade’Duappulo, Andi Sultan Daeng Raja, yang juga digelari Karaeng Kacamata, dikukuhkan sebagai Karaeng Gantarang pada usia 28 tahun, yang menurut kabar adalah Karaeng termuda di seluruh Bantaeng saat itu. Hal pertama yang dilakukannya sebagai karaeng dalah memperbaiki infrastruktur pertanian yang merupakan sumber penghasilan dari 90% rakyatnya. Selain itu, beliau juga meletakkan landasan yang kuat akan pendalaman keagamaan masyarakat Gantarang. Beliau juga lah yang mendirikan Masjid Raya Ponre yang halamannya menjadi petilasan akhir beliau.
Aktif pada Pusaran Sejarah Bangsa
Sementara menjabat sebagai Karaeng Gantarang, Andi Sultan Daeng Raja masih menyisihkan waktunya untuk tetap berada pada pusaran pergerakan bangsa dan mengiringi kelahiran Republik Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan. Pendidikan dan fasilitas yang diterimanya sebagai bangsawan tidak lantas membuaikannya dalam kesenangan dan ketidakpedulian, tetapi dimanfaatkan sepenuhnya sebagai modal dasar demi untuk kemerdekaan bangsanya. Andi Sultan Daeng Raja mengkhususkan hadir secara fisik dalam setiap momen penting perjuangan bangsa. Ketika berlangsung Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, Andi Sultan Daeng menyempatkan hadir mewakili Jong Celebes untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda bersama 750 pemuda se-Nusantara di Batavia. Pada saat tokoh-tokoh nasional berkumpul mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus 1945, Andi Sultan Daeng Raja, bersama GSSJ Ratulangi dan Andi Pangerang Pettarani, ikut merumuskan naskah proklamasi yang kemudian dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, Andi Sultan Daeng Raja menggalang koordinasi dengan seluruh raja dan datu di Sulawesi Selatan untuk menghalau tentara NICA di awal Desember 1945 sampai kemudian tertangkap di bulan yang sama dan diasingkan selama lima tahun ke Menado.
Rupanya, pengkhianatan selalu menyertai sejarah orang-orang besar, tak terkecuali pada jalan perjuangan Andi Sultan Daeng Raja. Karaeng yang teramat dicintai rakyatnya ini rupanya tak mampu mengelak dari pengkhianatan kerabatnya, seorang yang di kemudian hari diolok-olok sebagai Belanda hitam; Andi Abdul Gani atau Karaeng Gani yang oleh NICA diangkat sebagai penjabat Karaeng Gantarang. Berkonspirasi dengan pasukan NICA yang dipimpin Kapten Raymond Westerling, Karaeng Gani memihak NICA dalam pembunuhan massal di Bantaeng dan seluruh wilayah sulawesi yang terkenal sebagai peristiwa pembantaian korban 40,000 jiwa di tahun 1948. Hampir seluruh kerabat laki-laki dari Andi Sultan Daeng Raja terbunuh pada peristiwa itu. Dikemudian hari, saat tercapai kesepakatan penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia, Karaeng Gani ikut meninggalkan Gantarang dan kemudian memilih menetap di Belanda.
Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda tahun 1949, Andi Sultan Daeng Raja kembali dari pengasingannya dan meneruskan kembali tugas sebagai Karaeng Gantarang selama setahun hingga meletakkan jabatan di tahun 1950. Oleh pemerintah jasanya ternyata masih diperlukan, tahun 1951, Andi Sultan Daeng Raja ditetapkan sebagai Bupati Bulukumba hingga tahun 1952, kemudian menjadi bupati Bantaeng hingga tahun 1956. Tahun 1957, Andi Sultan Daeng Raja terpilih menjadi anggota Konsituante hingga pembubarannya di tahun 1959. Pada hari jumat, 17 Mei 1963, bangsawan Gantarang yang tak mengenal gentar ini wafat di RS Pelamonia, Makassar dan dimakamkan di belakang Mesjid Raya Ponre, Bulukumba berdampingan dengan makam ayahandanya, Passari Petta Tanra.
Sebelum mangkat, Andi Sultan daeng Raja sempat meninggalkan tiga wasiat kepada putranya, Andi Sappewali; pelihara kejujuran, lindungi orang tertindas, dan jangan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, cukup di belakang Mesjid Raya Ponre.
Nilai
Lazimnya saat membaca sebuah biografi, selain menikmati alur kronik yang runut, kedirian kita berusaha mengais sesuatu yang memiliki nilai. Nilai yang cukup penting untuk menjadi pegangan hidup sosok yang di-biografikan. Nilai yang dicoba didownload untuk dipatrikan menjadi nilai pribadi pembacanya. Sejalan dengan adagium yg menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, maka membaca biografi adalah salah satu pencarian guru yang paling efektif juga, dengan mensubtitusi pengalaman sosok dalam biografi itu menjadi pengalaman pribadi berkerangka pengetahuan literatur (literal?). Mengutip dari David Siegel, biografi diceritakan untuk mendistribusikan nilai dari karakter seseorang yang menjadikannya menarik dan dapat dijadikan pegangan hidup buat manusia lainnya. Nilai yang kita bisa reguk dari sejarah hidup Andi Sultan Daeng Raja bisa kita ambil papa tiga petuahnya sebelum mangkat; kejujuran, keberpihakan pada korban kezaliman, dan kesahajaan. Hal yang teramat mudah kita hapal di luar kepala, namun teramat sulit untuk konsisten menerapkannya, terutama di saat berbenturan dengan banyak kepentingan hidup.
Sejak kanak-kanak, kita yang akrab dengan buku pelajaran selalu mendefinisikan pahlawan sebagai orang yang menjadi martir karena sesuatu yang diperjuangkannya, yakni nilai dan cita-cita yang mewakili orang banyak. Walaupun kadang nilai yang diperjuangkan adalah nilai pribadi yang secara kebetulan beririsan dengan kepentingan orang banyak, dan oleh penulis sejarah, kepentingan majemuk inilah yang dikedepankan sebagai dasar konsensus untuk mentahbiskan status pahlawan. Karena tentu saja, nilai kemanusiaan yang dihasilkan dari sebuah perjuangan bisa menjadi milik publik yang bebas untuk dipakai kemudian, dan dianggap sebagai bagian penting dari akumulasi perjuangan menuju satu bangsa yang merdeka, sehingga karenanya layak diperhitungkan oleh dunia internasional. Oleh pemerintah, pahlawan secara administratif adalah orang-orang yang karena jasa-jasanya kepada negara pernah disematkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra sehingga berhak menyandang gelar Pahlawan dan sekiranya meninggal, jasadnya boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Untuk penegasan kepahlawanan dan mungkin untuk mensosialisasikan ke masyarakat, nama pahlawan itu kemudian dijadikan nama jalan. Tapi ditengah kerumuman masyarakat yang makin banyak urusannya, nama pahlawan yang disematkan pada jalan di sekitar mereka kemudian hanya menjadi sekedar nama, sekedar landmark yang tidak berarti apa-apa selain sebagai penanda alamat saja.
Sekedar Nama Jalan?
Selain keluarganya, mungkin tak banyak yang mengenal sosok pahlawan Gantarang, walaupun namanya kemudian diabadikan sebagai nama jalan protokol di pusat kota Bulukumba dan di daerah Mallimongang Makassar, berdekatan dengan Monumen Korban 40,000jiwa. Keterbatasan literatur tentang Karaeng ini mungkin menjadi alasan mengapa sedikit demi sedikit kisah perjuangan beliau semakin tergerus. Dalam buku-buku sejarah, tidak banyak diceritakan tentang beliau walaupun Pemerintah Indonesia telah mengukuhkan beliau sebagai Pahlawan Nasional tahun 2002. Hanya ada satu buku biografi yang secara khusus mengulas kisah perjuangan beliau yang diterbitkan tahun 1981 oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Itupun hanya buku tipis 87 halaman, yang tentu saja hanya memuat kronik sejarah yang tak detail. Sayang sekali bahwa kesempatan untuk menggali lebih dalam pikiran dan etos perjuangan beliau tidak sempat digali secara mendalam oleh penulis saat itu, saat dimana beberapa saksi hidup perjuangan beliau masih hidup. Hingga saat ini setelah 26 tahun sejak buku itu terbit, belum ada upaya penerbitan kembali kisah hidup beliau. Mungkin beberapa saat lagi nama beliau kemudian hanya akan terkenang sebagai nama jalan saja, itupun kalau tidak ada rencana pemerintah untuk merombak tata penamaan jalan dan sebagainya, sejalan dengan makin maraknya pengembangan kota yang lebih bangga menggunakan nama asing untuk menarik konsumennya.
- Hulppest Commis = pembantu komisioner
- Agent Welsetboedel Kamer = pegawai rendahan
- Ambtenaar = pegawai pemerintah
- Ade’ Duappulo = kumpulan pemuka adat berjumlah 20
- Saoraja = istana kerajaan