Friday, March 09, 2007

Sewaktu masih kanak-kanak di Pannampu, rumah saya sering menjadi tempat persinggahan (transit) para pabbalu lipa’ ini, karena kebetulan Makassar merupakan juga pelabuhan penyebeerangan ke pulau-pulau lainnya di seluruh Indonesia. Tujuan utama mereka Kalimantan, Papua, atau Sumatera. Setiap mereka datang, aroma khas lipa’ sabbe (sarung sutera) dan lipa’ cello (sarung berbenang non sutra) selalu menjadi kenangan tersendiri, selain tentu saja kelakar para pabbalu lipa’ yang terkenal pandai bercerita sambil berguyon. Lipa’-lipa’ tak ber merk (no brand) ini dibungkus dalam kain sarung besar, pernah sewaktu kanak-kanak itu saya mencoba mengangkat gulungan yang mungkin mencapai 400 sarung, namun tak pernah berhasil.
Beberapa malam yang lalu saya kedatangan tamu, La Nuhong, paman saya yang tinggal di Ujung Baru, Sempangnge, Wajo, bersama 3 orang rekan nya dari Sempangng. Mereka adalah pabbalu lipa’ yang sedang berjualan di sekitar Balikpapan. Awalnya saya kaget mereka datang, dengan mengendarai 2 sepeda motor ber-plat DD (plat nomor Sulawesi Selatan), mengunjungi rumah saya di Balikpapan. Kekagetan saya dikarenakan kenyataan bahwa masih ada pabablu lipa’ di zaman serba praktis ini. Sepengetahuan saya, Sarung sutra asal Sengkang sudah banyak dijual di mall-mall di seluruh Indonesia, bahkan saya pernah menemukan seorang Batak berjualan Sarung Sutra asal Sengkang di atas jembatan penyeberangan UKI, Jakarta Timur. Jadi kita hanya perlu ke pasar/mall untuk mencari sarung sengkang, tak perlu menunggu kiriman saudara di kampung, apalagi menunggu pabbalu lipa’ datang berkunjung ke rumah.
Ngobrol dengan pabbalu lipa’ ini menjadi hiburan tersendiri buat saya yang jauh dari kampung, selain mereka pandai berkelakar, juga banyak informasi unik yang diceritakan mengenai negeri-negeri yang mereka pernah jelajahi untuk berjualan sarung ini. Untuk setiap kali keluar ’mabbalu lipa’, mereka bisa membawa 400 lembar sarung dengan nilai sekitar Rp 10 juta. Untuk menghabiskan lipa-lipa’ ini, rata-rata mereka harus bepergian selama 3-5 bulan. Saya sendiri tak bisa membayangkan betapa beratnya sarung-sarung itu mereka angkut ke tempat-tempat jauh. Sarung-sarung ini mereka peroleh dari seorang yang mereka panggil ”Boss”, mungkin sama artinya dengan Juragan atau Majikan. Sang Boss inilah yang memodali dengan lipa’lipa’ dan membiayai perjalanan dan akomodasi para pabbalu lipa’. Karena alasan keselamatan, mereka selalu bepergian mabbalu lipa’ dalam satu rombongan berjumlah 5-10 orang.
Dengan tetap dalam satu rombongan, mereka bisa saling membantu sekiranya ada diantara pabbalu lipa’ ini yang mengalami kesulitan. Namun demikian, mereka juga tetap berprinsip untuk tidak melakukan kesalahan dan perbuatan yang merugikan masyarakat di tempat mereka mabbalu lipa’. Di zaman sekarang, mereka juga difasilitasi dengan sepeda motor yang juga dibawa dari kampung, berbeda dengan zaman sebelum tahun 90-an dimana mereka menjual sarung hanya dengan berjalan kaki, atau menumpang bis umum. Namun dengan begitu, para pabbalu lipa’ ini tetap harus melunasi biaya serta modal sarung yang mereka terima dari Boss setelah mereka pulang ke kampung.
Hampir setiap jengkal tanah di Indonesia ini pernah disinggahi oleh pabbalu lipa’ ini. Namun tempat favorit mereka adalah daerah yang memiliki komunitas bugis seperti Riau, Jambi, Papua dan Kalimantan Timur.
Malam itu mereka bercerita tentang tempat bernama Kuala, 70 km dari Balikpapan, yang baru saja mereka singgahi seminggu untuk berjualan sarung. Umumnya mengeluh bahwa sarung yang mereka jual kalah bersaing dengan sarung ’cicilan’ yang didagangkan oleh orang lokal. Cara pembayaran dengan beli kontan membuat sarung mereka tak begitu diminati oleh pembeli, walaupun secara kualitas, harga dan originalitas, sarung mereka cukup bagus. Selembar sarung dihargai Rp. 40.000 – 70,000, dengan margin keuntungan bisa 50-100%. Rata-rata mereka bisa berhasil menjual 2-5 lembar sarung setiap harinya. Yang membeli sarung ini umumnya adalah orang-orang bugis juga yang masih percaya pada originalitas dan kualitas sarung sengkang ini.
Kisah sedih juga mereka sempat ceritakan berkaitan dengan rekan mereka yang tewas dibantai penduduk lokal di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam perjalanan pulang kembali ke Sengkang, rekan mereka itu bertabrakan dengan seorang pemuda lokal yang sedang mabuk. Malang bagi sang pabbalu lipa’, rupanya kerumunan penduduk lokal yang dirasuki amarah kemudian menghakimi nya sampai meninggal, kepala bagian belakangnya pecah karena dihantam balok besar. Akhirnya rekan2 mereka sesama pabbalu lipa’ mengambil jenazahnya dan dibawa pulang ke Sempangnge. Saya teringat akan paman saya juga, yang mengalami nasib sama, di bunuh di daerah Barru ketika berjualan sarung. Resiko lain yang kadang menimpa mereka adalah dirampok atau ditipu oleh penduduk setempat. Kadang penduduk setempat membeli sarung-sarung mereka dengan cara mencicil/utang, namun sampai saat para pabbalu lipa’ ini hendak pulang ke kampung, penduduk lokal itu menghilang dan tidak membayar sisa utang nya. Mungkin itulah sebabnya para pabbalu lipa’ lebih mengutamakan pembayaran langsung daripada mencicil.
Resiko besaR yang mereka hadapi selama mabbalu lipa’ menjadi tak ada artinya ketika harus berhadapan dengan tuntutan hidup untuk menafkahi keluarga. Umumnya, disamping berprofesi sebagai pabbalu lipa’, mereka juga adalah petani dikampungnya. Saat menunggu musim panen atau bercocok tanam, mereka keluar mabbalu lipa’. Sawah dan ladang diserahkan pengelolaannya kepada istri atau keluarga dekat, sedang para lelaki pemberani ini mencari peruntungan lain dengan mabbalu lipa’. Tapi saya tak tahu, sampai kapan para pabbalu lipa’ ini eksis di bumi nusantara. Penjualan langsung di pasar dan mall sedikit demi sedikit memperkecil peran mereka di masa depan.
Kini, pabalu lipa’ rupanya tidak lagi banyak memasarkan sarung khas dari sengkang itu, mereka lebih menyukai menjual sarung non tenunan buatan pabrik-pabrik tekstil di Jawa. ketika saya iseng-iseng membongkar isi tas berisi sarung-sarung itu, saya agak kecewa karena sarung yang dijajakan rupanya tidak satupun sarung tenun asli Sengkang. Mungkin mempertimbangkan faktor praktis dan keuntungan, mereka tak lagi menjajakan sarung tenun asli sengkang. Sarung buatan pabrik tekstil di Jawa ini umumnya tidak luntur dan awet, serta harga nya murah. Dibandingkan dengan sarung tenun asli sengkang, yang sering luntur, dan mahal harganya, tentunya merupakan komoditas yang agak sulit mendapat tempat di hati para konsumen. Saya membayangkan, kalau kemudian pabbalu lipa’ ini sudah mulai mengubah komoditas dagangnya dengan buatan pabrik tekstil Jawa, suatu saat mereka akan cepat tersingkir, juga lipa sabbe khas sengkang itu…



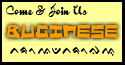


Pabbalu lipa itu sebutan untuk para penjual sarung keliling itu, ya? Menarik sekali. Saya suka dengan posting dengan tema-tema macam ini. Antara kultur, ekonomi, dan daerah. Semoga kedepannya para pabbalu lipa ini tetap terus ada dan dapat lebih dihargai oleh masyarakat. Bagi saya mereka adalah pahlawan budaya ^^
Ohya, saya orang Balikpapan juga, kok. Asalnya juga dari Kampung Baru Ulu. Salam kenal.