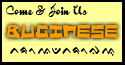Oleh Nirwan Ahmad Arsuka
Oleh Nirwan Ahmad Arsuka
Hari itu, I Mangngadaccinna Daeng I Ba’le’ Sultan Mahmud Karaeng Pattingalloang (KP), tengah berdiri menyambut angin semilir dan gemerisik ombak Makassar. Saya bayangkan, di sisi Perdana Menteri Kesultanan Gowa itu, di bawah matahari Februari 1651, berdiri menantunya: I Mallombassi yang kelak menjadi Sultan Hasanuddin. Putera KP, Karaeng Karungrung, tampak mencermati buku di tangannya. Sejumlah tubarani (satria) dari istana Tallo dan benteng Sombaopu terlihat juga di sana. Sebagian di antaranya berbaur dengan wajah-wajah Makassar, Bugis, Malaka, Jawa, Campa, Johor, Minang, Patani, India, Cina, Portugis, Spanyol, Denmark, Perancis dan Inggeris.
Di pertengahan abad 17 itu, Makassar adalah bandar paling ramai dan paling kosmopolit di Negeri-negeri Bawah Angin belahan Timur. Dikitari sejumlah benteng yang dibangun dan diperluas sejak seratusan tahun yang silam, di bawah Raja Gowa IX Karaeng Tumapa’risi’ Kallona, pusat kerajaan Gowa – Sombaopu – menjadi kota antarbangsa dengan keragaman penduduk tertinggi dalam 600 tahun sejarahnya.
Ketika Malaka jatuh di bawah hantamam meriam Portugis pada 1511, sejumlah satria Melayu yang menampik kekalahan tersebut, pindah beramai-ramai ke Siang (Pangkajene Kepulauan). Mereka kemudian hijrah ke Sombaopu setelah mendapat jaminan perlindungan tertulis dari Raja Gowa X Karaeng Tunipalangga. Jaminan yang memberi kesempatan kepada segala jenis manusia yang melintas di Nusantara hak menegakkan semacam hukum ektrateritorial itu, adalah jaminan pra-Eropa pertama di Nusantara.
Suaka niaga itu menjadi sorga pelarian, kali ini oleh Portugis, setelah Malaka jatuh ke tangan Belanda pada 1641. Sejak itu, Makassar menjadi tempat persinggahan utama Portugis di Nusantara. Sekitar 3000 orang Portugis menetap di tengah kota, lengkap dengan 4 buah tempat ibadat Kristen. Sebelumnya, pada 1613, Inggeris sudah membangun sebuah pabrik, disusul Denmark lima tahun kemudian. Para pedagang Cina dan Spanyol, dengan tetap menyimpan kenangan pada tanah leluhur, tampak membangun jaringan bisnis dan berdiam di kota itu masing-masing sejak 1619 dan 1615.
Satu-satunya bangsa yang jarang berkeliaran di Sombaopu di sekitar tahun 1651 itu justeru Belanda, kendati jauh sebelumnya mereka juga diperkenankan membangun pabrik dan kantor dagang. Itu adalah buah dari perang dingin yang diawali sejak fajar abad 17 dari dua musuh bebuyutan di samudera timur Nusantara. Dengan segala cara, Kompeni ingin menguasai seluruh jalur laut rempah-rempah dan menegakkan monopoli yang diamanatkan Parlemen (Staten Generaal) Republik Persatuan Nederland. Makassar tegak dengan kalimat keramat mare liberum yang pada 1615 ditegaskan Sultan Alauddin Raja Gowa XIV: Tuhan menciptakan bumi dan lautan. Tanah dibagi-bagikan di antara manusia dan samudera diperuntukkan bagi semuanya. Tak pernah terdengar bahwa pelayaran di lautan dilarang bagi seseorang, bagi satu kaum.
Sampai tahun 1651 itu, perang terbuka belum meledak di antara dua kekuatan maritim ini. Konflik memang sudah berlangsung cukup lama dan di beberapa tempat darah bertumpahan. Di awal April 1615, sejumlah pembesar Gowa diculik kapal Enkhuisen. Penculikan itu tadinya diawali dengan undangan bersahabat, jamuan makan, minum-minum, dilanjutkan dengan acara bakutikam dan pertempuran berdarah tak seimbang. Beberapa satria Gowa terluka dan tewas. Penawanan yang diatur oleh kapten Dirck de Vries dan kepala kantor VOC di Sombaopu Abraham Sterck, memantik murka Makassar. Pada Desember 1616, kapal Belanda pertama yang ke Australia, de Eendracht, tersesat di Selat Makassar. Dituduh masuk wilayah Gowa tanpa ijin, dan juga karena dendam atas penawanan licik hampir dua tahun sebelumnya, Makassar menyita de Eendracht dengan segenap isinya: bersama ke 16 nyawa awaknya yang tersisa.
Kedua kejadian di atas, ditambah dengan pemblokiran Sombaopu yang tak berarti banyak bagi phinisi Makassar oleh armada Belanda di bawah Gijsbert van Lodestein (1634), bantuan pelaut-pelaut Makassar kepada rakyat Maluku melawan keganasan VOC dalam Pelayaran Hongi, beserta sekian kejadian panas lainnya, umumnya memang bisa diselesaikan dengan perjanjian. Sebuah perjanjian diplomatik utama ditandatangani 26 Juni 1637 oleh Sultan Alauddin dan Gubernur Jenderal Antonio van Diemen. Di dalamnya antara lain disebutkan bahwa Gowa tak akan berdagang di tempat-tempat yang menjadi musuh Kompeni dan Belanda dilarang membangun kantor dagang di Makassar.
Sampai 1651, tak sepotong bangunan pun diperkenankan berdiri di Sombaopu sebagai kantor VOC, justeru ketika seluruh bangsa lain di dunia, diperkenankan berkembang dan dilindungi. Padahal jaringan dagang adidaya dunia abad 17 itu justeru sudah mulai menguasai Nusantara setelah melibas Tanjung Harapan, Coromandel, Srilangka dan Malaka, dan terus merambah ke Utara sampai ke Taiwan dan Jepang. Meski demikian, perdagangan Makassar dengan Belanda dalam beberapa hal masih berjalan. Seperti Amsterdam, Antwerpen, Venesia atau Genoa, kota Sombaopu saat itu juga hidup dan bergerak dengan semangat kapitalisme awal yang sedang marak di Eropa Barat dan masih menyisakan denyut di Mediterania. Bahkan Sultan pun berniaga. KP juga pedagang besar yang menjalin bisnis dengan Maluku, Portugis, dan Belanda di Batavia. Transaksinya bertebaran sampai ke Manila, Thailand, Golconde (India) dan semua tempat yang bisa dicapai armadanya.
Pada 22 Juli 1644, KP menyerahkan kepada kapten kapal Belanda Oudewater kayu cendana senilai 660 real dan satu daftar pesanan barang yang diurai rinci oleh Denys Lombard dalam karya besarnya Nusa Jawa: Silang Budaya. Bahkan Belanda pun menyebut pesanan KP sebagai rariten, barang langka. Selain peta-peta navigasi dunia yang selama berabad-abad digolongkan sebagai harta dan rahasia negara, yang terpenting di antara rariten itu adalah bola dunia dengan keliling 4 meter, ditambah atlas bumi dan teropong bintang yang seba terbaik di dunia.
Setelah menanti 7 tahun, datanglah pesanan yang ditunggu-tunggu. KP jelas sangat mengidamkan barang itu. Ia memerlukan datang sendiri menjemputnya. Beberapa tahun sebelumnya, sejumlah pesanannya sudah ada yang tiba. Tapi kali ini, yang datang adalah instrumen yang bahkan para cendekiawan Eropa sebagian besar hanya bisa memimpikannya.
Persis di salah satu hari di pertengahan Pebruari itu, sebuah kapal Belanda membuang sauh di bandar Sombaopu. Kabar akan merapatnya kapal dagang itu, seperti biasa, sudah menyebar ke seluruh kota. Banyak penduduk, yang seperti KP, juga datang meramaikan bandar. Tapi berbeda dengan Sang Pabbicara Butta, sebagian penduduk mungkin hanya ingin melihat benda aneh berukuran besar. Di antara penduduk itu mungkin ada yang ingat pada sebuah kejadian 9 tahun yang silam, tepatnya 16 Mei 1642. Pedagang Portugis yang sudah mereka kenal lama, Wehara (Francisco Vieira de Figueiredo) membawa binatang aneh berbelalai yang besarnya hampir separuh rumah: gajah.
Bisa jadi karena melihat binatang mitologis anak benua India itu kesepian, ditambah minat besar mengetahui hewan-hewan ajaib dari belahan dunia lain, sekaligus untuk melengkapi koleksi satwa yang ada, di antaranya adalah antelop Afrika dan kuda-kuda Asia, KP mengirim surat ke Gubernur Jenderal di Batavia. Di surat yang diterima pada 4 Juni 1648 itu tercantum permintaan binatang tunggangan para sultan dan nabi dari gurun Arabia: sepasang unta jantan dan betina.
Apapun niat hati mereka yang berkumpul di bandar Sombaopu hari itu, orang-orang dengan berbagai raut muka, warna kulit, bahasa dan busana itu, semuanya, terutama sang perdana menteri, saya bayangkan sedang tegang. Mereka menanti didaratkannya bola dunia terbesar yang mungkin dilihat oleh Asia Tenggara di pertengahan abad 17 itu. Bola dunia dengan garis tengah 1,3 meter itu memang sangat mengesankan. Joan Blaeu sendiri yang langsung membuatnya, dan itulah bola dunia terbesar yang dihasilkannya. Kartograf mashyur ini, antara lain pernah membuat instrumen pengamat bintang untuk astronom Denmark Tyco Brahe. Instrumen tersebut misalnya adalah revolving azimuth quadrant. Menurut Brahe, alat setinggi 3 meter ini skalanya akurat sampai seperempat menit busur. Antara lain dengan instrumen ini, meski masih memegang pandangan klasik geosentrisme, Brahe menegakkan reputasinya sebagai astronom terbesar dunia di masanya.
Joan adalah generasi kedua keluarga pembuat peta dan bola dunia yang paling ternama di Amsterdam – di masa itu peta-peta keluaran Amsterdam diakui sebagai yang terbaik sedunia. Ayahnya, Willem Janszoon Blaeu, jauh sebelumnya sudah tenar dengan karya peta Belanda (1604), peta dunia (1605-06) dan Het Licht der Zeevaerdt (Sang Cahaya Navigasi), sebuah atlas bahari yang menyebar ke seluruh dunia dengan sejumlah edisi, bahasa dan judul yang berbeda. Sekitar 1635, hidrografer VOC ini menerbitkan volume pertama atlas jagad yang diberi judul Atlas Novus. Dengan antara lain memanfaatkan dan meyempurnakan sejumlah peta karya kartograf legendaris Gerard Mercator, inilah atlas terbaik di jamannya. Ia mencakup peta-peta paling mutakhir dari seluruh jengkal bumi yang diketahui. Tampaknya inilah atlas yang dimaksud dalam daftar pesanan barang langka KP.
Ketika pesanan bola dunia dan yang lain dari KP mencapai Amsterdam, bagai api di padang rumput kegemparan menjalari kalangan terpelajar di Belanda. Dengan Aula Kota-nya yang penuh pualam dan melampaui arsitektur Gothik, Belanda yang relatif toleran terhadap pendapat-pendapat non-othodoks menjadi daerah suaka para intelektual yang mengungsi dari penyensoran di tempat lain di Eropa. Belanda di pertengahan abad 17 adalah rumah bagi filsuf besar Yahudi Baruch Spinoza, yang dikagumi Einstein; bagi Rene Descartes, tonggak penting sejarah filsafat dan matematika; bagi John Locke, pemikir politik yang secara filosofis kelak mempengaruhi revolusi Amerika lewat Paine, Hamilton, Adams, Franklin dan Jefferson. Tak pernah sebelumnya dan setelahnya, Belanda begitu dimegahkan oleh sekumpulan seniman, ilmuwan, filsuf dan matematikawan. Zaman itu adalah era pelukis ternama Rembrandt, Vermeer dan Frans Halls; Antonie Van Leeuwenhoek, penemu mikroskop; Grotious, pembangun Hukum Intenasional. Salah satu anggota komunitas ini adalah dramawan dan penyair terbesar Belanda, Joost van den Vondel, yang oleh daftar pesanan rariten KP, tergerak mempersembahkan sajak untuk penguasa dari Timur itu.
Lahir di Colegne, Jerman, Vondel mempengaruhi sastra Eropa antara lain dengan karya Gysbrecht van Aemstil (1637), dan Lucifer (1654) yang konon meninggalkan jejak pada epik terbesar Inggeris, Paradise Lost John Milton (1667). Selama kebangkitan Belanda melawan Spanyol, Vondel menampilkan sejumlah sajak yang merayakan kejayaan Belanda Bersatu. Namun, drama Palamedes (1625) yang mengangkat tema kemartiran religio-politik, membangkitkan kejengkelan kaum Calvinis. Ia lalu bergabung dengan kaum pembangkang menentang Calvinisme dogmatik dan kelak pada 1641 berpindah iman ke Katolik Roma.
Eulogiumnya kepada KP mungkin berasal dari pengalaman gelapnya dengan Eropa. Inilah benua di mana para raja dan bangsawan mengabaikan ilmu karena tak punya kontribusi langsung pada ekspansi wilayah, para pendeta dan uskup menentang ilmu karena menganggap kebenaran mutlak sudah ditemukan. Sementara itu, para ilmuwan mengembara atau dikucilkan, dan hanya bisa berkarya dengan baik di bawah segelintir penguasa yang berpikiran terbuka. Pemikir bebas yang sial, seperti Michael Servetus dan Giordano Bruno, hanya mengakhiri hidup dan petualangan intelektualnya di atas kobaran api unggun. Vondel mungkin melihat kombinasi menakjubkan dalam diri KP: seorang penguasa agung di sebuah kesultanan besar yang sekaligus seorang pemburu ilmu yang sangat bersemangat. Larik-larik dan persahabatan intelektual yang melampaui agama dan benua berikut tercantum di Volledige Dichtwerken.
Dien Aardkloot zend ‘t Oostindische huis
Den grooten Pantagoule t’huis,
Wiens aldoorsnuffelende brein,
Een gansche wereld valt te klein.
Men wensche dat zijn scepter wass’,
Bereyke d’eene en d’andere as,
En eer het slyten van de tyd
Dit koper dan ons vriendschap slyt.
“Bola dunia itu, Perusahaan Hindia Timur
Mengirimkannya ke istana Pattingalloang Agung
Yang otaknya menyelidik ke mana-mana
Menganggap dunia seutuhnya terlalu kecil.
Kami berharap tongkat kekuasaannya memanjang
Dan mencapai kutub yang satu dan yang lain
Agar keusuran waktu hanya melapukkan
Tembaga itu, bukan persahabatan kita.”
Dengan agak susah payah, bola dunia itu mendarat dan diarak menuju istana. Sepanjang jalan, anak-anak dengan pakaian longgar bersorak di bawah matahari Celebes yang benderang, yang sedikit dijinakkan oleh stratocumulus sisa-sisa Musim Barat. Bola dunia besar itu akhirnya masuk ke ruang belajar KP yang luas dihiasi lonceng raksasa.
Seperti sebagian besar buku di ruang itu, lonceng itu dipesan langsung dari Eropa. Mungkin KP ingin melihat bagaimana bunyi genta dari menara yang berbeda bisa mengoyak Eropa dalam perang agama yang berdarah. Perang serupa pernah juga ia alami. Yang pasti ia tertarik pada akustik dan hukum-hukum penjalaran gelombang suara. Di kamar itu juga ditemukan sejumlah prisma segitiga yang memungkinkan dekomposisi cahaya, yang jelas membiaskan minat KP pada sifat-sifat geometris cahaya dan citra-citra visual. Sejauh manakah orang yang siang malam menenteng buku fisika dan matematika ini bergulat dengan ide penjalaran gelombang cahaya? Di sekitar tahun itu juga, di belahan bumi yang lain, Fransisco Maria Grimaldi, seorang fisikawan Italia, oleh sejarah sains Eropa dicatat menemukan hukum difraksi optis dan menegaskan ide spekulatif gelombang cahaya.
Di ruang belajar yang luas itu, Sang Perdana Menteri menerima sejumlah tamu asing, bercakap dan berdebat dalam bahasa sang tamu. Pastor Alexander de Rhodes yang mencipta transkripsi huruf Latin untuk bahasa Vietnam, adalah salah satu di antaranya. Bersama misionaris katolik Jesuit itu, KP mendiskusikan banyak hal, dari gerhana bulan hingga ke karya bruder Spanyol ordo Dominikan, Luis de Granada. Sebagai misionaris saleh, bapa pastor Belanda tentu saja mencoba segala daya mengkristenkan KP. Pertemuan itu memang berlanjut beberapa kali dan berakhir dengan persahabatan dan kepergian bapa misionaris membawa catatan penuh pujian yang akan dikabarkannya ke dunia.
Dari pastor de Rhodes-lah antara lain diketahui betapa besar minat KP pada agama, sejarah dan peradaban Eropa, betapa kaya perpustakaannya yang dipenuhi buku dan radas ilmiah. Minat yang nyaris tak terbatas pada semua ilmu yang diketahui saat itu, khususnya Agama dan Ilmu Alam, menunjukkan sesuatu yang melampaui rasa ingin tahu teoritis. Dua yang terakhir itu adalah pengetahuan paling ambisius yang ditemukan manusia: keduanya mengklaim semesta raya seisinya sebagai subyeknya dan percaya bahwa ada penjelasan terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam ruang dan waktu semesta.
Yang aneh adalah bahwa dalam catatan itu tak disebut adanya buku-buku sastra di ruang KP itu. Mungkinkah karena ia memang kurang mencintai seni? Ataukah karena para pengabar kecendekiawanan KP, umumnya pedagang dan misionaris, dua jenis manusia yang dalam bentuknya yang karikatural suka memandang curiga pada imajinasi dan seni? Kita ingat Meneer Droogstoppel, karakter ciptaan Multatuli dalam Max Havelaar: pedagang sukses ini mencemooh puisi dan roman, dan menganggap teater sebagai dusta. Kita ingat rahib buta Jorge, tokoh karya Umberto Eco dalam The Name of The Rose: penunggu perpustakaan biara itu mengutuk lelucon dan imajinasi atas nama iman yang tak terbantah.
Yang pasti, seluruh buku Luis de Granada, dalam bahasa Spanyol, ada di perpustakaan itu. Saya bayangkan karya penyair Jazirah Iberia dan sastrawan Eropa lainnya, para pemimpi yang memberi isi pada kata Renaissance, juga ada di sana. Mungkinkah di antaranya terselip Dante, Luis Vaz de Camões, Rabelais, Shakespeare atau Miguel de Cervantes? Jika ia membaca Don Quijote dan Sancho Panza, apa gerangan reaksinya? Sukakah ia pada karya yang dianggap sebagai novel moderen pertama dalam sejarah sastra dunia ini? Apa jawabnya atas distingsi Cervantes antara kebenaran puitis dan kebenaran historis; atas pembedaan Don Quijote antara kehidupan satria dan kehidupan cendekiawan?
Saya bayangkan, sejak detik pertama masuknya bola dunia di perpustakaan itu hingga separuh tenggelamnya matahari di Selat Makassar, KP terus mendekam di ruang itu. Ia mengasyikkan diri memutar-mutar bola tembaga tersebut, membandingkannya dengan atlas Blaeu dan dengan pengalamannya sendiri, mencocokkan peta dengan teritori. Awalnya ia mencermati letak Sombaopu di antara dua kutub, lalu menandai segenap wilayah kesultanan Gowa dengan hegemoni yang paling berpengaruh antara Jawa dan Luzon. Kemudian ia mencari letak kota-kota yang pernah didengarnya, kota-kota yang puluhan tahun sudah hidup di benaknya.
Sambil menelusuri kota-kota tersebut, bergerak dari samudera ke samudera, dari benua ke benua, ia teringat bagaimana dulu sejumlah Belanda datang menghadap. Mereka tak habis mengerti kenyataan ini: di Jepang, di bawah dinasti Ieyasu Tokugawa, merekalah satu-satunya bangsa Eropa yang boleh ada di negeri Matahari Terbit yang justeru sedang menutup diri ke dunia; di Gowa, merekalah satu-satunya bangsa Eropa yang tak boleh punya kantor di seluruh wilayah kesultanan yang justeru membuka diri ke dunia. Dengan sopan utusan gubernur jenderal itu memohon ijin membangun kantor dagang. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa istimewa Eropa, Belanda-belanda itu membeberkan betapa lemahnya Spanyol yang mereka kalahkan dalam Perang 80 tahun, dan betapa kejinya Inggeris yang memenggal rajanya.
KP lalu mencermati London dan membayangkan parlemen, disokong Oliver Cromwell, akhirnya memancung Charles I. Ia terkenang pada Raja Gowa XIII Karaeng Tunipasulu’. Naik tahta pada usia 15, dengan semaunya ia memecat pembesar-pembesar Gowa, merusak kemerdekaan federasi Bate Salapanga dan membunuh orang-orang yang tak disenanginya. Gelaran lain baginda adalah I Pakere’ Tau (Sang pemotong manusia). Baginda memerintah dengan cara memalukan, seakan lupa bahwa seorang leluhurnya, Raja Gowa VIII Tujallo ri Passukki, tewas ditikam dalam amukan seorang hambanya. Sang Hamba mengeksekusi rajanya setelah baginda sial itu tuntas menitahkan hinaan memalukan yang tak tertanggungkan. Menganggap cukup sepak terjang sewenang-wenang raja, rakyat dan dewan adat bergerak. Mereka memecat dan memakzulkan si Pemotong Manusia yang cuma bisa bertahta 3 tahun, dan membuangnya keluar kerajaan.
Usai mengunjungi kota-kota besar dunia, menebak pengetahuan penduduk benua-benua yang baru ditemukan, dan memastikan letak Westphalia tempat diakhirinya Perang 80 tahun yang melibatkan hampir seluruh Eropa, untuk kesekian kali ia disergap oleh sekaligus ekstasi dan agoni pengetahuan. Titik-titik bola dunia itu mengantarnya pada sebuah revelasi yang belum pernah ia alami. Kepingan-kepingan pengetahuan yang ditimbunnya bertahun-tahun, informasi-informasi yang dulu tampak tak saling berhubungan dan menolak disatukan, kini semuanya berubah. Segala macam informasi itu, bahkan yang sudah terlupakan dan tenggelam ke bawah sadar, bangkit berputar-putar bagai angin beliung yang kemudian mengorganisasikan diri menjadi sebuah dunia, sebuah semesta baru pengetahuan.
Di matanya, permukaan bola dunia itu tak lagi beku. Sejumlah titik api muncul di sana, membara dan mengecil. Batas-batas berubah, meluas dan menyusut. Dengan permukaan yang terus berdenyut dan bergerak cepat, seakan saling menjalin saling memangsa, bola dunia itu menjadi hidup merepresentasikan apa yang kelak dikenal sebagai Sejarah.
KP merasakan tubuhnya membesar. Kepalanya melembung menyedot seluruh bola dunia itu masuk ke dalamnya, bersatu dengan dirinya, memberinya rasa nikmat yang tak terlukiskan. Ekstase pengetahuan ini berlangsung beberapa detik, untuk kemudian diganti dengan perasaan longsor yang menakutkan. Dalam sekilas, KP dan bola dunia itu kembali terpisah. Kini ia yang merasa dirinya mengecil, sangat kecil, dan tersedot masuk sebagai sebuah bintik sepele di permukaan bola dunia tersebut. Ia debu tanpa arti dari jagat yang terus berputar dan berubah.
Ia paham betapa mininya negerinya, betapa tak berartinya Celebes. Ia tahu nenek moyang Makassar telah menjelajah jauh sampai ke Campa, Pantai Marege dan Madagaskar. Tapi itu belum berarti banyak dibanding penjelajahan Portugis, Spanyol, Belanda atau Inggeris. Merekalah yang membuktikan dunia ini bulat. Merekalah yang meyusun cermat peta-peta dunia dan membikin bola dunia raksasa. Saya bayangkan KP makin melihat secara berbeda negeri-negeri lain. Di benaknya terbentang antara lain sebuah gambaran mental yang sebelumnya telah dilihat Vondel. Vondel yang nasionalis melihat Amsterdam sebagai sumbu dunia: gudang-gudang besar sepanjang dermaga kota yang ditumpuki rempah-rempah dan kain cita dari Timur, berbagai kargo ikan dan paus dari Laut Utara dan Baltik, gula dari Hindia Barat serta tembakau dari Virginia dan Maryland.
KP tahu bahwa seluruh kota besar di dunia semuanya adalah sumbu dunia, kecuali Sombaopu. Pemahaman ini memberinya rasa perih yang bertahan lebih lama dari rasa nikmat yang tadi. Penyesalan mulai tumbuh pada usianya yang berangkat senja. Ia mungkin ingin juga berlayar mengelilingi Bumi, menyedot langsung pengetahuan dunia dari sumbernya. Ia tahu dari pedagang Eropa bahwa Colombus menemu Amerika pada 1492, bahwa Magellan bertolak keliling dunia pada 1519, disusul Francis Drake pada 1577. Yang pasti, ia ingin agar Sombaopu juga jadi sumbu jagat dan tak tenggelam oleh gelombang besar yang datang bersusulan dari luar, yang demi rempah-rempah bersedia saling menghancurkan dan mengorbankan apapun.
Rasa perih, sesal dan cemas yang bercampur-aduk itu tak banyak surut oleh ingatan pada naskah keahlian membuat meriam yang ditulis dalam bahasa Spanyol konon oleh Andreas Monyona. Naskah itu sudah diringkas dalam bahasa Makassar sejak 1635 dan kini, atas perintahnya, sedang dalam perampungan penerjemahan lengkap. Di masa dialah memang, tercatat memuncaknya kegiatan penerjemahan serangkaian risalah teknologi Eropa ke bahasa Nusantara. Tak ada negeri lain di wilayah yang kini bernama Indonesia yang melakukan penerjemahan sesistematis itu. Naskah-naskah pembuatan meriam, pabrikasi bubuk mesiu dan senjata diterjemahkan dari bahasa Spanyol, Portugis dan Turki.
Tapi ia tahu, untuk tumbuh dan berkembang menjangkau dunia dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar meriam dan benteng. Itulah kengototan untuk menjelajah, kerakusan pada pengetahuan-pengetahuan baru, ketakpuasan pada apa yang sudah dicapai, yang semuanya harus ditumbuhkan dan disebarluaskan. Ia memang terus memerintahkan Bugis-Makassar membangun keterampilan menggandakan dan membuat peta-peta serta jalur-jalur penjelajahan maritim, sebuah keterampilan yang juga unik di Nusantara. Tapi keterampilan kartografis serta teknologi militer dan transportasi laut yang sangat unggul itu, tak cukup menggerakkan Sulawesi menjelajah sampai ke kutub; melumpuhkan Belanda sampai ke Amsterdam dan membentangkan sendiri imperium yang melintasi benua untuk menjinakkan ekspansi imperium lain.
Mungkin karena segala hal yang mereka perlukan untuk hidup nyaman menurut sangkaan mereka ada semua di negeri ini. Maluku yang jadi obsesi ribuan tahun Eropa ada di samping, sementara mereka tidak merasa perlu berlayar menyelamatkan sukma belahan dunia lain. Seperti semua tempat di seluruh kawasan yang dekat equator, Makassar saat itu adalah juga firdaus: tanah-tanah yang demikian indah yang membuat upaya membayangkan sebuah surga yang lain menjadi suatu kemustahilan kognitif. Penduduk asli tanah-tanah itu hidup dengan dengan lazuardi yang belum dilintasi sejarah dan samudera yang belum terseret sorga. Para pendatanglah yang memperkenalkan mereka dengan konsep dan detail asing itu.
Berabad-abad masyarakat dengan masa silam pendek ini, hidup dalam kekinian yang kekal, mencintai tubuh, sawah dan lautnya yang membentang, dan hanya punya pemahaman tegas tentang kehormatan (siri’) dan konsep samar dunia orang mati. Teknologi militer memang bisa dipelajari cepat, tapi butuh waktu lama dan sejarah yang keras untuk belajar merawat rasa hormat pada masa lampau seraya membangun ambisi dengan rencana-rencana agung ke masa depan.
Saya bayangkan KP merenungkan orang-orang yang bersedia menghambur memburu totalitas dan tak gentar membawa segala hal ke ujung yang ekstrim, yang tak ragu menyeret seluruh dunia dalam kancah perang ide-ide, yang menumbuhkan dalam dirinya hasrat dan kesadaran imperial untuk dibentangkan tidak cuma dalam ruang tapi juga dalam waktu. Mungkinkah ia teringat sebuah legenda Jerman yang diceritakan orang Inggeris tentang seorang doktor yang bersedia menukar jiwanya kepada Iblis demi mendapatkan kekuasaan pengetahuan yang memungkinkannya menghasilkan karya-karya yang memuaskan sukma selama 1000 tahun?
Hanya azan magrib yang menarik KP kembali ke Makassar. Usai menunaikan Isya ia membawa pelita ke menara Maccini Somabala (observasi layar). Bulan di atas Sombaopu adalah benda langit yang selalu diminatinya. Sejak kanak-kanak ia memang sering mengamatinya dengan mata telanjang. Kebutuhan menghitung hari-hari penting Islam dan mencatat peristiwa penting kerajaan dalam kronik lontara yang tak ada tandingannya di Nusantara, membuatnya kian akrab dengan benda itu. Tapi mata telanjang bukanlah tandingan teleskop.
Setahun setelah kedatangan bola dunia, tibalah di Makassar sebuah radas ilmiah yang mengubah sejarah astronomi dunia: teleskop prospektif Galileo. Itu adalah hasil dari upaya KP pada tahun 1635 meyakinkan raja sebelumnya, untuk membuat kesultanan Gowa memiliki teleskop terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Gowa perlu mendekatkan jarak langit.
Saya bayangkan di lensa pengintip itu, mata KP menjelajahi bulan yang awalnya dilakukannya dengan setengah berdebar. Ia mencari lagi di permukaan itu jejak-jejak Tumanurunga ri Tamalate, bidadari yang konon diturunkan dari khayangan dan menjadi cikal-bakal kerajaan Gowa. Seperti diduganya, jejak itu tak ia temukan. Ia lalu memusatkan diri pada penampakan fisik bulan yang menyedot perhatiannya cukup lama. Tergerakkah ia menggambar secara tepat permukaan bulan? Di Jerman, Johannes Hevalius oleh sejarah sains Eropa dicatat mulai membuat peta-peta akurat permukaan bulan di sekitar tahun KP mengarahkan teleskopnya ke lazuardi.
Hampir pasti KP tergerak menyusun peta lunar. Itu membuatnya mengamati bulan lebih intens. Tiba-tiba ia teringat kembali pada sebuah bulan lain sekian tahun yang silam, sebuah purnama yang bersinar di atas Bone. Di Oktober 1643 itu, KP sedang memimpin balatentara Makassar sebanyak 40.000 parajurit.
220-an tahun sebelum Abraham Lincoln mencantolkan isu abolisi perbudakan dalam Perang Saudara Amerika Serikat, Raja Bone XIII La Ma’daremmeng Sultan Muhammad Saleh sudah mengobarkan perang pembebasan budak yang barangkali kasus pertama di Asia Timur dan Tenggara. Dulu, Ayahanda KP, Karaeng Matoaya Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenanga ri Agamanna, mendatangi Bone beserta seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan dan mengajaknya masuk Islam. Alasannya adalah bahwa agama dan sistem nilai lama tak akan cukup memadai menopang kerajaan-kerajaan tersebut menghadapi perubahan-perubahan besar yang datang menderu dari luar. Begitu La Ma’daremmeng naik tahta, ia bergerak lebih jauh dari Matoaya dan menginginkan ajaran Nabi dilaksanakan setuntasnya. Meski sangat vital bagi kehidupan sosial ekonomi kerajaan, perbudakan harus dihapuskan. Negeri-negeri jazirah selatan Sulawesi yang masih mempertahankan perbudakan, harus diperangi, termasuk Gowa.
Awalnya Gowa ragu menghadapi sepak terjang Bone yang sangat keras, kendati sejumlah bangsawan pelarian Bugis telah mendesak Sombaopu mengambil tindakan. Di antara para pelarian itu, adalah We Tenrisoloreng Datu Pattiro, ibunda La Ma’daremmeng, yang terpaksa hijrah sebagai bentuk penentangan atas aturan tanpa kompromi anandanya. KP kemudian mengirim utusan untuk memperoleh kepastian apakah aturan keras penghapusan budak itu memang mengikuti seruan Nabi, ataukah sekedar keputusan La Ma’daremmeng pribadi. Kegagalan Bone menjawab hal ini, membuat KP berangkat memimpin pasukan besar yang terbentuk dari gabungan balatentara Gowa, Wajo, Soppeng dan Sidenreng. Dan setelah sekian ratus malam yang penuh cahaya, setelah sejumlah pertempuran ganas yang melelahkan, pasukan besar itu akhirnya menaklukkan Bone dan menawan La ma’daremmeng, sebuah kekalahan besar yang dalam kronik Bone dicatat sebagai awal dari diperhambanya Bone selama 17 tahun. Kelak kesultanan Bugis terbesar itu, dipimpin oleh Arung Palakka Sang Raja Berambut Panjang, memanfaatkan kulminasi perseteruan Gowa dengan Belanda untuk membebaskan diri dari kekuasaan Sombaopu.
Puas mengamati purnama, KP mengarahkan teleskopnya ke bintik-bintik cahaya yang lain. Lensa itu membuatnya kian sadar bahwa langit malam bukanlah sekedar kegelapan raksasa yang diperindah kelap-kelip cahaya. Langit malam adalah kehidupan yang disusun dari perubahan dan keteraturan. Semua benda langit bergerak menggeser letaknya, mengubah susunan dan konstelasinya, dalam keteraturan yang kekal, yang menjadi sahabat sejati lunas phinisi melintasi abad demi abad.
Beberapa cahaya di langit sudah dikenal baik para peniti gelombang. Cahaya yang masuk ke dalam teleskop KP, menghadirkan sejumlah kawan baru yang dulu tak bisa dilihatnya tegas dengan mata telanjang. Terlihatkah Io, Europa, Ganymede dan Callisto – bulan-bulan Yupiter yang ditemukan Galileo Galilei 40 tahun sebelumnya? Terlihat jugakah olehnya Konstelasi Cassiopeia yang ditemukan Brahe pada 1572? Bagaimana dengan Nebula Orion atau Neptunus? Sukakah ia pada konstelasi zodiak yang peta langitnya disusun Jodocus Hondius pada 1615?
Sebagian besar benda langit saat itu belum beroleh nama seperti yang dinomenklaturkan kini. Akan dinamai apakah benda-benda yang baru dikenalnya itu? Memberi nama bukanlah sekedar sebuah tindak taksonomis untuk membedakan sebuah benda dengan yang lainnya sekaligus memberinya tempat dalam tatanan benda-benda. Nama yang disematkan adalah ekstensi dari diri si pemberi nama, sejarah dan kebudayaannya, aspirasi-aspirasinya yang paling dalam, harapan-harapannya yang paling membubung: tindakan esensial pembangunan dunia simbolik yang mengukuhkan posisi pemberi nama di tengah semesta.
Pemberian nama selalu bermula dengan pengenalan, dan pengenalan yang mendalam menuntut perhatian panjang. Tetapi data perubahan yang dikumpulkan lewat waktu dan radas ilmiah yang mahal, bisa sekadar menjadi tumpukan tanpa arti. Kekuatannya akan muncul hanya bila ditata oleh dua hal: sistem logika formal yang diekspresikan dalam geometri Euklides dan jalinan hubungan sebab-akibat yang ditegaskan dalam eksperimen sistematik. Metode penggabungan data inderawi dengan logika dan eksperimen ini dirumuskan oleh Bapak Empirisme Francis Bacon di abad yang sama dengan KP, sang makhluk pertama di Asia Tenggara yang memahami makna matematika dalam ilmu-ilmu terapan. Kelak metode penggabungan itu terbukti menjadi jantung kekuatan sains dan teknologi mengubah dunia ke tataran yang sama sekali baru.
Tak inginkah KP membagi sensasi intelektual yang merekah lewat pertemuan dan pengenalan antara dirinya dengan benda-benda langit itu? Menilik semangatnya menyebarkan pengetahuan militer dan, sebelum jadi perdana menteri, membujuk Sultan membeli radas ilmiah mahal, bisa disimpulkan: ia ingin. Itu artinya ia harus membangun institusi – mungkin menjadikan menara Maccini’ Sombala semacam observatorium umum. Segala instrumen ilmiah yang mahal, masih bisa dibeli selama perdagangan bebas tegak di lautan. Dari sini, perlu sejumlah langkah lagi ke institusi semacam Royal Society London atau Académie des Sciences Paris. Dua organisasi yang ikut jadi kunci supremasi Eropa itu, diresmikan oleh Charles II dan Louis XIV belasan tahun setelah KP menghabiskan malamnya dengan teleskop di Maccini’ Sombala.
Untuk kesekian kali, teleskop KP kembali ke bulan. Benda terbesar di langit malam itu mengingatkannya lagi pada Tumanurunga ri Tamalate. Saya bayangkan ia merenungkan percakapan Tumanurunga dengan raja-raja kecil Bate Salapanga. Itu sebuah kontrak sosial politik yang unik dalam sejarah Nusantara. Sebuah kontrak yang membentuk Gowa-Tallo dari federasi sembilan negeri. Prihatinkah ia pada apa yang terjadi dengan Bate Salapanga? Awalnya lembaga ini adalah lembaga perwakilan rakyat. Tapi perlahan-lahan ia merosot menjadi sekedar perangkat kerajaan. Para anggotanya tak punya wewenang membuat undang-undang dan peraturan. Mereka tak dapat menjalankan pemerintahan di seluruh kerajaan dan harus tunduk menjalankan segala perintah raja. Bahkan belakangan mereka pun tak lagi menjadi badan penasehat. Raja memerintah secara mutlak yang sabdanya merupakan undang-undang.
Terpikirkah oleh KP bahwa sebulan setelah kematiannya, sebagai penguasa baru, Sultan Hasanuddin – karena sejumlah pertimbangan, terutama mungkin kemudahan mengeksekusi kebijakan – menetapkan bahwa dirinya sendirilah yang merangkap perdana menteri? Tindakan itu mengakhiri sebuah aturan quasi-konstitusional pembagian kekuasaan dalam kerajaan kembar Gowa-Tallo, pembagian yang dalam sejarah kelak terbukti sebagai dasar kokoh kebesaran kesultanan maritim itu.
Belasan tahun setelah sentralisasi kekuasaan dan kematian KP, menara Maccini’ Sombala dan kompleks istana Sombaopu akhirnya memang jatuh ke tangan balatentara sekutu Belanda, Bone, Buton dan Ternate. Bahkan ketika KP masih hidup, konstelasi dan dinamika ekonomi politik Nusantara yang antara lain memarakkan penyelundupan dan strategi harga selektif oleh para pedagang lokal yang menampik monopoli VOC, membuat Sombaopu menjadi kota di mana harga rempah-rempah menjadi paling murah di dunia, lebih murah dibanding di Maluku sendiri. Karena larangan berdagang di Sombaopu, Belanda harus mendapatkan komoditas vital ini di tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Ini membuat segenap upaya besar puluhan tahun Belanda menaklukkan Tanjung Harapan, Srilangka, Malaka dan Batavia untuk menguasai jalur rempah-rempah, menjadi kesia-siaan yang memalukan. Bangsa-bangsa lain, termasuk musuh-musuh tradisional Belanda di Eropa, tak perlu mengorbankan habis armada dan prajurit untuk mendapatkan rempah-rempah dan komoditas penting lain yang lebih murah di Sombaopu.
Jika kita percaya bahwa rempah-rempahlah yang menggerakkan gelombang besar penemuan benua-benua baru yang kelak mengeras menjadi imperialisme dan kolonialisme itu, maka dengan ringkas bisa dibilang bahwa persis di depan gelombang besar inilah Makassar membentangkan dadanya. Di pertengahan abad ke 17 itu, bukan Eropa sang penakluk dunia, juga bukan Maluku pulau rempah-rempah, melainkan Gowa yang pada akhirnya menentukan harga rempah-rempah di Bumi. Upaya akbar berabad-abad dan penuh darah untuk menguasai jalur maritim dunia, menjadi tak ada artinya selama Makassar dan benteng istana Sombaopu masih menegakkan supremasi.
Benteng istana paling perkasa yang pernah dibangun di Nusantara itu, hanya dapat direbut adidaya dunia abad 17 dengan sekutunya melalui pertempuran teramat berat yang oleh prajurit-prajurit senior Belanda, sebagian di antaranya veteran Perang 80 Tahun yang dahsyat itu, digambarkan sebagai pertempuran yang bahkan tak pernah terjadi di sejarah Eropa sendiri. Bersama ratusan pucuk meriam – yang pembuatannya dimungkinkan oleh kengototan KP – di antaranya Anak Makassar, konon meriam terbesar yang pernah dibikin di Nusantara, Gowa beberapa kali nyaris menumpas Sekutu. Antara lain akibat sekian pengkhianatan dari dalam, Makassar akhirnya hanya bisa mempersembahkan pada Belanda dan sekutunya sebuah perang yang paling brutal dan paling dahsyat yang pernah dilakukan VOC di dunia sejak didirikan. Para panglima Makassar yang belum puas dengan persembahan itu dan tak menerima sikap takluk istana, Seperti Karaeng Galesong dan Karaeng Bonto Marannu, menyebar keluar melanjutkan perang di laut dan daratan yang lain.
8 tahun setelah wafatnya KP yang dimakamkan di Bonto Biraeng, terbit Atlas Maior Joan Blaeu. Dengan 600 halaman rangkap peta dan 3000 halaman naskah, karya ini menjadi pencapaian kartografis-artistik yang sampai kini tak tertandingi. Pada bagian Peta Dunia, terlihat dua sosok besar (gbr.1). Di hemisfer Barat tampaknya nabi kartografi dunia modern awal: Mercator. Di langit Timur, di atas Asia, tampak KP tengah menetapkan jarak Celebes dari Kutub Utara. Dua pemikir yang dengan caranya sendiri menyusun dunia, kini bekerja di langit, di antara dewa-dewi mitologis Yunani Purba, di antara planet-planet Tatasurya.
Pustaka:
- Anthony Reid, Charting The Shape Of Early Modern Southeast Asia (Chiang Mai: Silkworm Books, 1999)
- Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Jakarta: Gramedia, 1996)
- Sagimun MD, Sultan Hasanuddin (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).
Baca Artikel Selengkapnya..!
 Dari Pa'balu' Lipa' Sabbe ke Pangempang Muara, dari SempangngE ke Mangkupalas
Dari Pa'balu' Lipa' Sabbe ke Pangempang Muara, dari SempangngE ke Mangkupalas Di penghujung tahun 1980an, selepas SMA di SempangngE, La Caba’ turut beserta pemuda-pemuda sekampungnya massompe (merantau) ke luar Sulawesi, dengan menjadi pabbalu lipa’ sabbe, pedagang sarung Sutera (lipa sabbe’) berkeliling Indonesia. Umumnya, daerah yang dituju adalah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, atau Papua. Namun ada juga yang berjualan lipa sabbe di pulau Sulawesi juga, dari Makassar, Takalar, sinjai, luwu, Palu, Banggai, sampai ke Gorontalo. Beberapa dari mereka sempat juga menjejakkan kakinya di daratan Jawa, namun tidak banyak, mungkin dikarenakan keberadaan Sarung Pekalongan atau kain batik yang juga mendominasi waktu itu. Disetiap kota, biasanya para pabbalu lipa’ ini menyewa sepeda motor utnuk membantu mobilitas mereka untuk menjajakan lipa sabbe nya dari kampung ke kampung. Di dekade
Di penghujung tahun 1980an, selepas SMA di SempangngE, La Caba’ turut beserta pemuda-pemuda sekampungnya massompe (merantau) ke luar Sulawesi, dengan menjadi pabbalu lipa’ sabbe, pedagang sarung Sutera (lipa sabbe’) berkeliling Indonesia. Umumnya, daerah yang dituju adalah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, atau Papua. Namun ada juga yang berjualan lipa sabbe di pulau Sulawesi juga, dari Makassar, Takalar, sinjai, luwu, Palu, Banggai, sampai ke Gorontalo. Beberapa dari mereka sempat juga menjejakkan kakinya di daratan Jawa, namun tidak banyak, mungkin dikarenakan keberadaan Sarung Pekalongan atau kain batik yang juga mendominasi waktu itu. Disetiap kota, biasanya para pabbalu lipa’ ini menyewa sepeda motor utnuk membantu mobilitas mereka untuk menjajakan lipa sabbe nya dari kampung ke kampung. Di dekade  sebelumnya, para pabbalu lipa ini hanya berjalan kaki dari kampung ke kampung, kadang pekerjaan ini mengundang resiko tinggi, bahkan nyawa mereka. La Caba’ bertutur, dulu di tahun 1960-an, La Tellong bin Ompeng - kakak lelakinya lain ibu, dirampok dan dibunuh bersama rombongannya ketika mabbalu lipa’ di pedalaman Barru atau Sinjai, kuburannya tidak diketahui sampai sekarang.
sebelumnya, para pabbalu lipa ini hanya berjalan kaki dari kampung ke kampung, kadang pekerjaan ini mengundang resiko tinggi, bahkan nyawa mereka. La Caba’ bertutur, dulu di tahun 1960-an, La Tellong bin Ompeng - kakak lelakinya lain ibu, dirampok dan dibunuh bersama rombongannya ketika mabbalu lipa’ di pedalaman Barru atau Sinjai, kuburannya tidak diketahui sampai sekarang. Di penghujung tahun 1980an, selepas SMA di SempangngE, La Caba’ turut beserta pemuda-pemuda sekampungnya massompe (merantau) ke luar Sulawesi, dengan menjadi pabbalu lipa’ sabbe, pedagang sarung Sutera (lipa sabbe’) berkeliling Indonesia. Umumnya, daerah yang dituju adalah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, atau Papua. Namun ada juga yang berjualan lipa sabbe di pulau Sulawesi juga, dari Makassar, Takalar, sinjai, luwu, Palu, Banggai, sampai ke Gorontalo. Beberapa dari mereka sempat juga menjejakkan kakinya di daratan Jawa, namun tidak banyak, mungkin dikarenakan keberadaan Sarung Pekalongan atau kain batik yang juga mendominasi waktu itu. Disetiap kota, biasanya para pabbalu lipa’ ini menyewa sepeda motor utnuk membantu mobilitas mereka untuk menjajakan lipa sabbe nya dari kampung ke kampung. Di dekade
Di penghujung tahun 1980an, selepas SMA di SempangngE, La Caba’ turut beserta pemuda-pemuda sekampungnya massompe (merantau) ke luar Sulawesi, dengan menjadi pabbalu lipa’ sabbe, pedagang sarung Sutera (lipa sabbe’) berkeliling Indonesia. Umumnya, daerah yang dituju adalah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, atau Papua. Namun ada juga yang berjualan lipa sabbe di pulau Sulawesi juga, dari Makassar, Takalar, sinjai, luwu, Palu, Banggai, sampai ke Gorontalo. Beberapa dari mereka sempat juga menjejakkan kakinya di daratan Jawa, namun tidak banyak, mungkin dikarenakan keberadaan Sarung Pekalongan atau kain batik yang juga mendominasi waktu itu. Disetiap kota, biasanya para pabbalu lipa’ ini menyewa sepeda motor utnuk membantu mobilitas mereka untuk menjajakan lipa sabbe nya dari kampung ke kampung. Di dekade  sebelumnya, para pabbalu lipa ini hanya berjalan kaki dari kampung ke kampung, kadang pekerjaan ini mengundang resiko tinggi, bahkan nyawa mereka. La Caba’ bertutur, dulu di tahun 1960-an, La Tellong bin Ompeng - kakak lelakinya lain ibu, dirampok dan dibunuh bersama rombongannya ketika mabbalu lipa’ di pedalaman Barru atau Sinjai, kuburannya tidak diketahui sampai sekarang.
sebelumnya, para pabbalu lipa ini hanya berjalan kaki dari kampung ke kampung, kadang pekerjaan ini mengundang resiko tinggi, bahkan nyawa mereka. La Caba’ bertutur, dulu di tahun 1960-an, La Tellong bin Ompeng - kakak lelakinya lain ibu, dirampok dan dibunuh bersama rombongannya ketika mabbalu lipa’ di pedalaman Barru atau Sinjai, kuburannya tidak diketahui sampai sekarang.